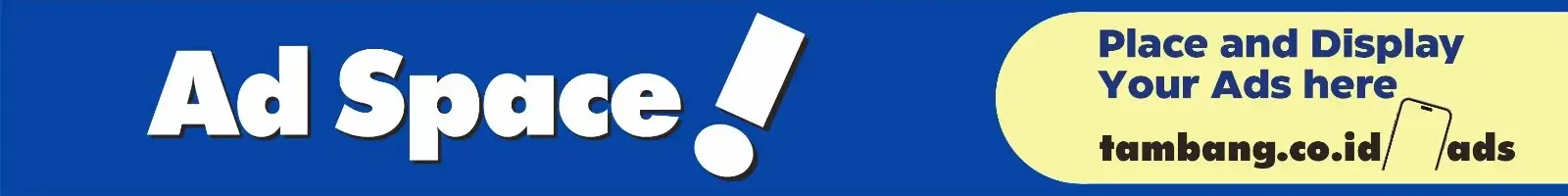Bersiaplah Harga Minyak Turun Lagi

HARGA minyak yang tinggi sudah lama kita keluhkan. Kita semua tentu masih ingat, menjelang akhir pemerintahan Presiden SBY, pada 2013, harga minyak sempat melangit. Ratusan triliun duit APBN harus dibelanjakan untuk membayar subsidi: menjaga agar harga bahan bakar minyak tetap terjangkau masyarakat.
Ketika itu, premium dihargai Rp 4.500 per liter. Minyak tanah, yang ditujukan bagi masyarakat lapis bawah, hanya Rp 2.500 per liter. Bahan bakar yang tak disubsidi, harganya jauh di atas: pertamax bisa mencapai Rp 10.000, dan minyak tanah Rp 12.000.
Perbedaan harga yang lumayan dalam itu membuat situasi jadi rawan. Beberapa kali kita menjumpai berita ihwal ditangkapnya pembeli minyak bersubsidi, yang menggunakan minyak murah itu untuk keperluan yang seharusnya menggunakan bahan bakar tanpa subsidi.
Yang beruntung akibat tingginya harga minyak adalah produsen minyak itu sendiri, plus industri turunannya, di antaranya jasa transportasi, keuangan, dan pemboran. Tentu saja pemerintah tempat industri itu berada juga menikmati untung dari pajak, terciptanya lapangan kerja, dan efek berganda lainnya.
Sejak 2014 harga minyak turun, dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam tempo kurang dari enam bulan, harga minyak turun hampir 50%. Bagi kita di Indonesia, efeknya langsung terasa.
Sisi positifnya, pemerintah membuat kebijakan baru di harga minyak. Harganya kini tak dipatok, melainkan subsidinya yang ditetapkan. Maka, kita bisa melihat harga minyak yang berayun-ayun turun naik mengikuti pergerakan harga internasional. Di awal pemerintahan Jokowi-JK, harga premium turun, tapi kemudian naik lagi. Postur APBN lebih sehat karena subsidi BBM mengempis drastis.
Harga minyak internasional yang murah punya dampak positif: harga di dalam negeri juga ikut turun. Biaya industri juga turun. Sayangnya, harga-harga tidak mengikuti turunnya harga. Berlaku rumus umum: harga boleh naik, tapi jangan harap turun.
Sayangnya, penerimaan pemerintah dari bagi hasil minyak, plus pajak, juga ikut berkurang. Dari pemantauan majalah TAMBANG di industri perminyakan, rendahnya harga minyak ternyata memiliki sisi mudarat yang tak kalah seramnya. Situasinya tak kalah buruknya dengan yang terjadi pada industri tambang dan mineral.
Bila Anda menelusuri industri penunjang jasa migas, banyak yang menyebut dua tahun terakhir ini, terutama 2015, sebagai tahun puasa. Dalam pertemuan buka bersama Ikatan Surveyor Indonesia, di kantornya, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, terungkap ada sebuah perusahaan jasa survei yang sudah menang tender pada Juni 2014, tetapi hingga sekarang kegiatannya belum dieksekusi, menunggu harga minyak membaik.
Pengalaman serupa dialami perusahaan survei lain, yang dinyatakan menang atas tender jasa survei pada November tahun lalu tapi hingga kini belum ada eksekusinya. Di pemberitaan kita melihat, raksasa jasa penunjang perminyakan, seperti Halliburton dan Schlumberger, mengalami nasib lebih suram: ribuan karyawannya dipangkas.
Sayangnya, rendahnya harga minyak belum akan berakhir. Bagi Anda yang bergerak di industri perminyakan, perjanjian nuklir Iran dengan Amerika dan sekutunya, yang akan diteken Selasa ini, mungkin menjadi alarm berbahaya. Dengan ditekennya perjanjian itu maka sanksi ekonomi terhadap Iran bakal dihapus.
Selama ini Iran mendapat sanksi ekonomi, walau dalam prakteknya negeri para mullah ini tetap menjual minyaknya dengan diam-diam, menggunakan mekanisme perdagangan rumit. Setelah sanksi diangkat, Iran bisa menjual minyaknya dengan terang-benderang. Media ekonomi Bloomberg memperkirakan harga minyak akan turun 15%, setelah Iran kembali mengekspor minyaknya.
Sebelum diberi sanksi, Iran memproduksi sekitar 2,3 juta barel minyak per bari. Kini, produksinya tinggal 1,3 juta barel. Bila sanksi dihentikan, dalam tempo 6-7 bulan produksi Iran diperkirakan pulih kembali. Artinya akan ada tambahan 1 juta barel minyak di pasaran minyak dunia.
Maka, bersiaplah sedari awal, harga minyak akan kembali turun.