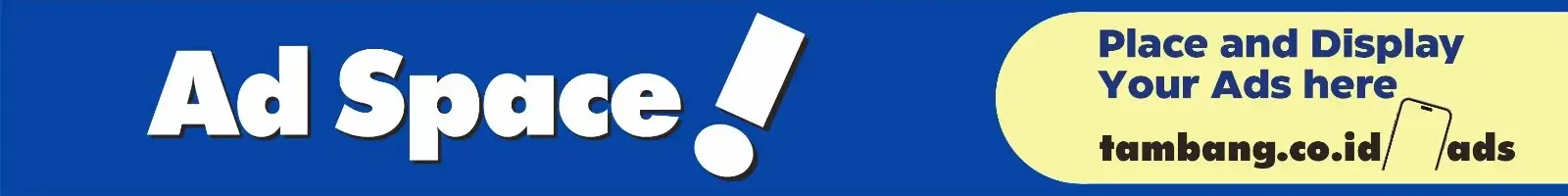Berbagi Jaringan Internet, Gaya Baru CSR di Masa Pandemi

Oleh: Dr Jannus TH Siahaan MA, MSi,
Pemerhati CSR dan Industri Pertambangan
Jakarta, TAMBANG – Selain ekonomi dan kesehatan, pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 hari ini. Tekanan kepada sektor pendidikan meningkat karena protokol kesehatan merekomendasikan agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau daring yang menuntut akses teknologi dan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai.
Sementara hanya sekitar 40% guru yang siap dengan teknologi. Kekurangan smartphone dan keterbatasan jaringan internet di daerah-daerah terpencil atau pedesaan turut menambah masalah. Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi terhambat, sebagian anak didik kesulitan mengakses materi sekolah maupun mengirim tugas-tugas.
Jika ketimpangan infrastruktur digital ini terus berlanjut maka Indonesia dapat mengalami kehilangan generasi (lost generation), atau minimal lonjakan ketimpangan pendidikan kota-desa.
Menyadari kondisi tersebut, pemerintah telah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah pada penguatan sarana digital di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, akan tetap menjadi prioritas dalam mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2021.
Namun, keterbatasan kapasitas fiskal memaksa pemerintah untuk mencari skenario alternatif misalnya melalui Public Private Partnership (PPP), maupun skema pelibatan swasta lainnya, jika tidak ingin serta merta menempuh jalur pembiayaan hutang.
Menghadapi situasi ini, industri ekstraktif dapat berkontribusi melalui kebijakan shared-use atau berbagi penggunaan infrastruktur digital. Strategi ini sekaligus menjadi titik tolak agenda reformasi tata kelola sumberdaya nasional.
Berbagi Infrastruktur, Berbagi Jaringan Internet
Industri ekstraktif seperti tambang, migas dan kehutanan, selalu membangun infrastruktur untuk mengembangkan sistem bisnis yang solid termasuk jika beroperasi di daerah terpencil.
Karena itu, kantor-kantor lapangan biasanya dilengkapi dengan jaringan internet modern di mana penggunaannya sering menjadi hak eksklusif perusahaan tersebut.
Shared-use adalah gagasan penggunaan infrakstruktur perusahaan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu fasilitas yang dapat menjadi objek berbagi ini adalah akses internet.
Dalam suasana krisis seperti sekarang ini, korporasi dapat memperluas jaringan internet mereka hingga ke desa-desa sekitar. Perusahaan juga dapat menyediakan ruang khusus di kompleks perkantoran mereka, beserta semua fasilitasnya, untuk para guru dan sekolah desa yang tidak memiliki internet.
Dukungan infrastruktur digital ini akan sangat membantu anak-anak untuk terus dapat mengakses pendidikan. Program ini juga akan sangat membantu peningkatan kapasitas tenaga pengajar. Inovasi berbagi infrastruktur digital akan memangkas ketimpangan dan mencegah ketertinggalan pendidikan di desa.
Yang terpenting, skema ini tidak membutuhkan dana pemerintah maupun pembiayaan hutang. Negara juga tidak perlu meyakinkan swasta melalui studi kelayakan yang mahal dan panjang.
Selama ada kemauan politik dari pemerintah, dan niat baik pelaku industri ekstraktif, program ini dapat terlaksana dengan mudah. Berbagi infrastruktur dapat menjadi bagian dari program CSR atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Reposisi Fungsi CSR
Banyak pihak selama ini salah kaprah dalam memahami tanggungjawab sosial perusahaan dengan melihat CSR sekedar sebagai kebaikan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Karena itu, kebanyakan industri memperlakukan CSR sebagai program residu yaitu alokasi sisa keuntungan dan bukan sebagai kebijakan strategis yang utama oleh industri.
Sebagian kalangan bahkan menganggap CSR hanya sebatas urusan bagi-bagi uang demi memuluskan operasi perusahaan. Dana CSR cenderung menyasar program-program pragmatis seperti berbagai macam bantuan sosial yang lebih banyak dinikmati oleh para pemburu rente dan ditunggangi politisi oportunis.
Hal ini diperparah oleh sikap pemerintah sebagai regulator yang gagap dalam melihat perkembangan kontemporer.
Perusahaan selalu saja ditempatkan sekedar sebagai agen pengeruk sumberdaya alam untuk menghasilkan revenue sebesar-besarnya, bukan sebagai mitra strategis untuk berbagi tanggungjawab dalam mengakselerasi kondisi sosial dan ekonomi desa.
Akibatnya, masyarakat yang semula mandiri dengan lahan sendiri menjadi tergantung terhadap perusahaan.
Data perekonomian tahun 2018 menunjukkan angka-angka ketergantungan terhadap sumberdaya tidak terbarukan, misalnya Kabupaten Mimika (85%), Kutai Timur (81%), Bengkalis (69%), dan Kutai Kertanegara (65%).
Kolaka sebagai salah satu penghasil nikel paling bersejarah di republik ini justru mengalami perkembangan memperihatinkan ketika hampir 50% perekonomiannya tergantung dari pertambangan. Padahal sekitar 15-20 tahun lalu angka ini hanya berkisar antara 8-15% saja.
BACA JUGA : Pemerintah Manfaatkan Dana CSR Tambang Bangun Jalan Di Kalsel
Situasi ini tentu saja sangat riskan. Ketika industri ekstraktif berakhir maka perekonomian lokal menjadi lumpuh akibat kehilangan penopang utamanya dalam sekejap.
CSR telah menjelma menjadi instrumen tukar menukar demi pencapaian sebuah tujuan kolonial yang dipoles secara lebih modern: memperoleh izin sosial untuk berusaha (social license to operate).
International Resource Panel PBB telah mengkonfirmasi kegagalan pendekatan social license to operate ini karena cenderung menjauh dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) dan tidak implementatif pada skala nasional.
Momentum Perbaikan Tata Kelola
Tata kelola industri ekstraktif selama ini telah jelas salah arah. Kedatangan modal sebaliknya menghilangkan kemandirian lokal, dan menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat rentan terhadap setiap gejolak ekonomi dan tekanan harga komoditas global.
Kejatuhan harga batubara dan minyak dunia misalnya dapat membuat masyarakat sekitar pertambangan jatuh miskin seketika. Investasi yang digadang-gadang dapat membantu perekonomian nasional justru telah menunjukkan gejala pertumbuhan semu.
Pendekatan primitif tersebut telah membuat investasi sektor ekstraktif bekerja mirip seperti narkoba: menciptakan ketergantungan sekaligus memberi efek candu (addictive) bagi masyarakat.
Pandemi harusnya menjadi momentum untuk keluar dari jebakan perspektif masa lalu dan mereformasi tata kelola sumberdaya nasional.
Program-program pemberdayaan harus mampu membuat masyarakat lebih mandiri dan mendorong diversifikasi ekonomi. Dalam skala yang lebih luas, program ini dapat dapat menyasar infrastruktur yang lain dan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan (perbankan), logistik, dan pasar.
Berbagi penggunaan infrastruktur pada dasarnya membuka potensi sosial dan ekonomi desa menuju masyarakat yang kompetitif. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai kompensasi terhadap penerimaan masyarakat dan izin pemerintah atas pengembangan proyek-proyek industri ekstraktif.
Dalam perspektif bisnis, program ini dapat memperkuat brand perusahaan dan meningkatkan citra korporasi, selain mempererat kerjasama dengan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat dan pemerintah lokal. Langkah ini merupakan perwujudan prinsip investasi yang bertanggungjawab sosial dengan tujuan akhir keberlanjutan (sustainability).