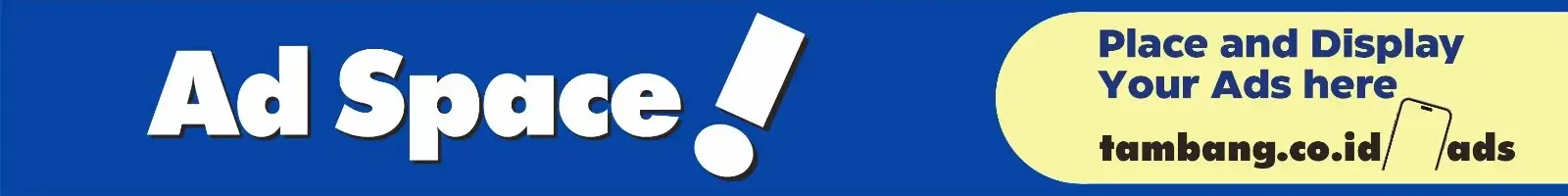Artikel Terkait

Menteri Bahlil: Bisnis Mineral Kritis Tetap Melalui Hilirisasi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemanfaatan mineral kritis harus tetap melalui proses hilirisasi dan tidak dijual dalam bentuk bahan mentah (raw material).

Perkuat Kesejahteraan Warga Lingkar Tambang, NHM Rampungkan Bedah Rumah ke-156
Komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat lingkar tambang kembali ditegaskan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Perusahaan tambang emas yang beroperasi di Halmahera Utara ini merampungkan program bedah rumah ke-156

BUMA Amankan Kontrak Dengan Adaro Untuk Tambang Tutupan Selatan Hingga 2030
Jakarta,TAMBANG,- PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), anak perusahaan utama PT BUMA Internasional Grup Tbk (IDX: DOID; “BUMA International Group”), hari ini mengumumkan penandatanganan kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia (“Adaro”). Kontrak yang berlaku mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2030 mengamankan keberlanjutan operasional BUMA di

PGN Masuk Jajaran 500 Perusahaan Asia-Pasifik Terbaik Versi Majalah TIME
Jakarta,TAMBANG,-Resiliensi bisnis PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) di tengah tantangan ekonomi global mendapatkan pengakuan internasional. Kali ini penghargaan tersebut datang dari Majalah TIME dimana PGN menempati ranking 288 dari 500 perusahaan di kawasan Asia-Pasifik dengan total Score 82,65. Dengan ini, PGN termasuk dalam 19 perusahaan