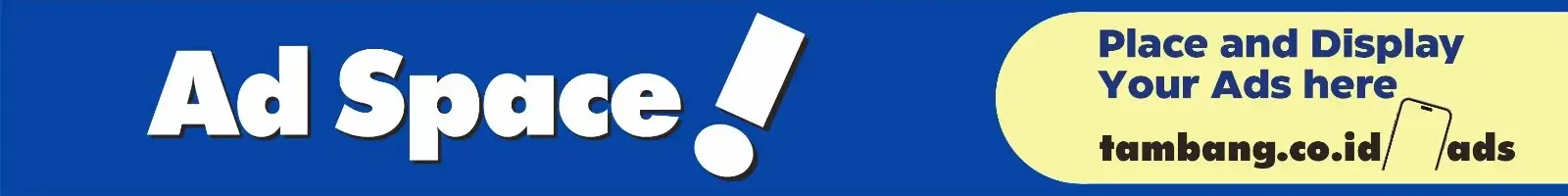Artikel Terkait

Ini Hasil Kajian LPEM FEB UI Terkait Kontribusi AMMAN Pada Makroekonomi Nasional Dan Regional
Jakarta,TAMBANG,- Aktivitas pertambangan dikenal sebagai kegiatan yang punya dampak ganda yang cukup besar. Ini dibuktikan lewat beberapa kajian yang dilakukan beberapa lembaga kajian. Salah satunya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Kali ini, LPEM FEB UI merilis hasil kajian dampak

Butuh 14 Hari, Pertamina "Pulangkan" Perwira yang Bekerja Di Irak dan UAE
Jakarta,TAMBANG,- PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil merelokasi 11 (sebelas) perwira yang bekerja di Basra, Irak dan 8 (delapan) yang berada di Dubai, UAE. Proses evakuasi dari Basra, Irak ke Jakarta membutuhkan waktu setidaknya 14 hari. Waktu yang panjang dibutuhkan karena adanya penutupan sejumlah bandara internasional,

Perang Israel–AS VS Iran Picu Kekhawatiran Minyak Global, Pasokan Indonesia Dinilai Aman
Berikut versi yang sudah diperbaiki dan dilanjutkan dengan gaya berita: Buntut perang antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran semakin melebar. Pasokan energi dalam negeri sempat menjadi kekhawatiran, terutama terkait potensi gangguan distribusi minyak dunia di kawasan Timur Tengah.

PLN EPI Pastikan Selama Lebaran Pasokan Batubara Untuk Pembangkit Aman
Jakarta,TAMBANG,- Hari Raya Idul Fitri 1447 H sudah semakin dekat. Kebutuhan listrik nasional diprediksi melonjak signifikan seiring mobilitas masyarakat yang tinggi. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan sistem pengelolaan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional berjalan dengan mekanisme yang terstruktur dan akuntabel. Ketahanan pasokan energi