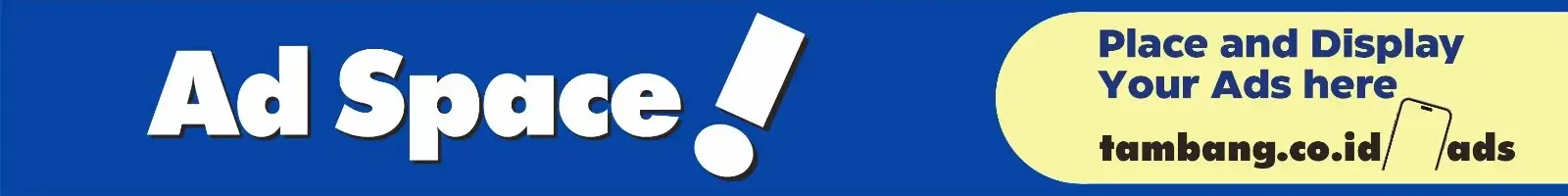PHE Raja Tempirai vs Golden Spike: Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke KY

Jakarta-TAMBANG. Pekara hokum yang melibatkan Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT) dan Golden Spike Energi Indonesia kini mulai menyeret Majelis hakim yang memutus perkara itu di PN Jakarta Pusat. Pihak PHE RT melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY) karena diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. PHE RT memasukkan laporan kepada Komisi Yudisial pada Senin, 23 Maret 2015, yang ditembuskan kepada Ketua MA dan Kepala Badan Pengawas MA.
Menurut M. Yahya Harahap, mantan Hakim Agung yang bertindak selaku kuasa hukum pelapor, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diduga melanggar beberapa ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan Peraturan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012. Di antara Kode Etik Hakim yang diduga dilanggar adalah berkaitan dengan kejujuran (Pasal 6), integritas (Pasal 9), dan profesionalitas (Pasal 14) Majelis Hakim dalam menangani proses perkara tersebut.
Sengketa antara PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI) melawan PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT) adalah kasus perkara luar biasa yang memiliki dampak serius. Kasus tersebut tidak hanya akan menimbulkan preseden buruk, namun bisa juga mengganggu iklim investasi.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto mengatakan, terganggunya iklim investasi terjadi akibat ketidakpastian hokum. Sengketa yang seharusnya diselesaikan melalui jalur arbitrase justru dilakukan melalui peradilan umum. Padahal banyak badan usaha, termasuk investor asing di Indonesia yang menjadikan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Alasannya, karena arbitrase lebih murah, bersifat final and binding karena tidak mengenal banding dan kasasi, serta mampu menjaga kerahasiaan (confidential). Dampak lain yang tak kalah serius juga akan dialami Pertamina. Jika terus diterpa kasus seperti ini maka kinerja BUMN tersebut bisa terganggu. Tentu saja hal ini sangat merugikan, karena Pertamina sebagai salah satu perusahaan yang sangat berpotensi menjadi perusahaan internasional. “Bisa bangkrut negara ini,” seru Hikmahanto.
Hikmahanto menegaskan, sengketa tersebut memang bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Sebab sesuai Perjanjian Bagi Hasil dimana PHE RT dan GSEI menjadi pihak, jika terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Apalagi yang menjadi dasar gugatan adalah wanprestasi seperti yang tercantum dalam perjanjian kerja samanya.
“Jadi sangat lucu jika kemudian Golden Spike menggugat lewat peradilan umum,” tuturnya.
Apabila para pihak dalam suatu perjanjian telah menyepakati klausul arbitrase, maka segala sesuatu sengketa yang timbul dari perjanjian, penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase. Tidak menjadi soal apakah dalam sengketanya wanprestasi, cacat kehendak (wilsgebrek, vitiated consent) atau perbuatan melawan hukum, dengan sendirinya menurut hukum jatuh menjadi yurisdiksi/kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikannya.
Dalil yang dijadikan majelis hakim untuk menyatakan berwenang dalam menangani gugatan Golden Spike, menurut Hikmahanto juga tidak tepat. Dalam putusan selanya, majelis hakim mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat bukan sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Bagi Hasil nya, namun sebagai pihak yang meneruskan perjanjian.
Menurut Hikmahanto, pengalihan pihak-pihak dalam perjanjian sama sekali tidak menggugurkan klausula arbitrase-nya. Dengan demikian, jika pada perjanjian tersebut yang menandatangani adalah Pertamina dan Golden Spike Indonesia Limited (GSIL) yang kemudian dialihkan masing-masing kepada PHE RT dan GSEI, maka hal itu tidak menjadi masalah sama sekali dan klausula arbitrase juga tetap berlaku mengikat kepada pihak-pihak penerusnya, pungkasnya.