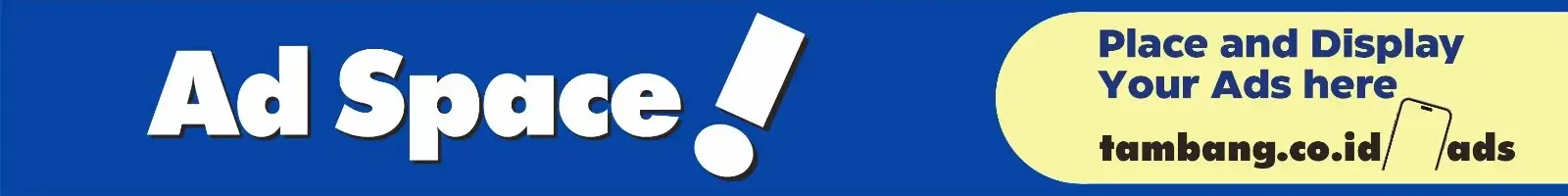Investor Asing Waspadai Aksi Korporasi Sinarmas

Jakarta - TAMBANG. Nama Eka Tjipta Widjaya belakangan kembali santer muncul di media massa, lewat aksi-aksi korporasi kelompok usaha Sinarmas Group yang didirikannya. Di sektor pertambangan pun, secara agresif Sinarmas berupaya mencaplok kepemilikan tambang-tambang besar. Padahal, sejarah pernah mencatat nama konglomerat terkaya ke-4 di Indonesia itu, sebagai pengutang obligasi terbesar di Asia.
Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) PT Dian Swastika Sentosa, Tbk (DSSA), anak usaha Sinarmas di sektor energi dan pertambangan, telah menyepakati transaksi tukar guling dengan perusahaan Singapura bernama United Fiber System, Ltd. Keputusan awal April itu mengalihkan kepemilikan saham Dian Swastika di PT Golden Energy Mines, Tbk (GEMS) sebesar 67% kepada United Fiber. Sebaliknya, Dian Swastika menukar saham bernilai sekitar US$ 1,42 miliar itu dengan kepemilikan atas United Fiber.
Kemudian, pada pertengahan April, Sinarmas lewat perusahaan baru bernama Asia Coal Energy Ventures (ACE) bergerak untuk mengambil alih induk usaha Berau Coal Energy. ACE mengajukan penawaran sebesar sekitar US$ 313 juta dalam rangka restrukturisasi Asia Resource Minerals.
Selain itu, logo Sinarmas juga tertera dalam dokumen PT Cakra Mineral, Tbk (CKRA) yang tengah mencoba mengakuisisi Cokal Limited (CKA). Cokal adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia, namun memegang beberapa konsesi tambang batu bara berkalori tinggi di Kalimantan. Kepada Majalah TAMBANG, petinggi Cokal sempat menyebut bahwa salah satu yang menjadikan tawaran itu menarik adalah nama Sinarmas, yang ada di belakang Cakra sebagai penjamin. Senin (27/4) lalu, perdagangan saham Cokal dihentikan sementara untuk menunggu pengumuman akuisisi tersebut.
Namun, artikel Bloomberg Selasa (28/4) mengingatkan para investor asing pada pengalaman buruk yang menimpa Eka Tjipta Widjaya saat krisis moneter akhir tahun 1990-an. Pada tahun 2001, perusahaan Asia Pulp & Paper dinyatakan sebagai perusahaan gagal bayar dengan utang sejumlah US$ 13,9 miliar. Itu termasuk utang obligasi senilai US$ 6,7 miliar, yang menjadi rekor terbesar Asia sepanjang sejarah.
"Investor harus waspada dengan sejarah restrukturisasi korporasi Indonesia, terutama dengan banyaknya penjadwalan ulang restrukturisasi. Investor juga harus paham dengan kerangka hukum pailit di Indonesia, yang paling memberikan keringan pada kreditur," ujar Brigitte Posch dari Babson Capital Management, sebagaimana dikuip Bloomberg.
Peringatan senada diungkapkan Hal Hirsch dari Alvarez & Marsal Inc, yang menyebut bahwa Indonesia bisa seperti 'labirin korporasi berbahaya bagi investor dan regulator' karena kurangnya transparansi. "Sejarah berulang dan memberikan pelajaran, bahkan dalam bisnis,"pungkas Hirsch.